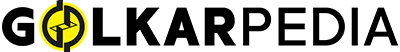Berita Golkar – Pagi yang cerah, namun saya tersenyum getir melihat gaduh yang tak habis-habisnya ngalor-ngidul di media sosial soal kebijakan bioetanol mixing 10 persen. Awalnya saya kira publik akan membahas aspek energi terbarukan, emisi karbon, atau strategi fiskal. Tapi yang terjadi malah sebaliknya: muncul meme, olok-olok, bahkan nada rasis yang menjurus ke personal. Sasarannya: Pak Bahlil Lahadalia.
Rasanya seperti menonton debat publik yang kehilangan topik utama—energi—dan malah sibuk menghakimi siapa yang bicara. Lucunya, kebijakan yang seharusnya jadi tonggak menuju clean energy malah berubah jadi bahan gosip. Padahal, substansi kebijakannya sederhana dan masuk akal.
Pemerintah ingin mencampur bensin dengan etanol—alkohol hasil fermentasi tanaman seperti tebu atau singkong—sebanyak 10 persen. Tujuannya bukan cuma soal lingkungan, tapi juga fiskal.
Indonesia kini mengimpor sekitar 42 juta ton bensin per tahun, dan subsidi energi kita tembus Rp186 triliun pada 2024. Kalau sebagian bensin itu diganti etanol, hitung-hitungannya jelas: impor berkurang, subsidi bisa ditekan, defisit neraca perdagangan sedikit bernapas.
Pak Bahlil sebenarnya sedang bicara soal masa depan energi nasional. Saat dia memaparkan ide itu di Simposium 100 Ekonom (INDEF dan CNBC), arahnya terang: menggeser ketergantungan dari energi fosil menuju energi terbarukan sambil membuka peluang hilirisasi pertanian.
Kalau bioetanol jadi bahan bakar, petani tebu, jagung, dan singkong mendapat pasar baru. Di situlah ide multi-track policy bekerja—energi, pertanian, dan fiskal saling menopang.
Tapi publik, seperti biasa, lebih tertarik pada siapa yang bicara ketimbang apa yang dibicarakan. Lalu muncul pertanyaan klasik: apakah kendaraan kita siap memakai bensin E10?
Nah, ini yang sering disalahpahami. Secara teknis, E10 adalah bensin dengan kandungan etanol 10 persen.
Hampir semua kendaraan bermesin bensin keluaran tahun 2011 ke atas sebenarnya sudah kompatibel. Data dari European Automobile Manufacturers Association (ACEA, 2021) dan Department for Transport Inggris menyebut 95 persen mobil bensin aman memakai E10.
Etanol memang punya sifat sedikit rewel: ia mudah menyerap air (higroskopik) dan bisa korosif terhadap material logam atau karet tua. Jadi, kendaraan lama—terutama produksi sebelum 2005—bisa bermasalah jika tangki, selang, atau segelnya belum tahan etanol.
Namun mesin modern yang memakai fuel injection, electronic control unit (ECU), dan material tahan alkohol tidak akan bermasalah. Soal performanya memang sedikit berkurang dari bensin murni; efisiensi bahan bakar bisa turun sekitar 1 persen. Tapi itu harga kecil untuk emisi yang lebih bersih dan ketahanan energi yang lebih baik.
Lagi pula, negara-negara lain sudah jauh di depan: India bahkan memakai E20 sampai E30, Jepang sejak lama memadukan biofuel, dan Amerika Serikat sudah menjadikannya standar nasional. Kalau Indonesia terus sibuk bertanya “sudah siap atau belum,” ya kita akan terus jadi penonton dalam lomba energi hijau global.
Ironisnya, ketika Pak Bahlil menjelaskan soal E10 di Universitas Muhammadiyah Malang, beberapa mahasiswa justru meneriakinya “hoaks.” Padahal, data dan grafik yang ia bawa bukan hasil khayalan. Itu data empiris, bersumber dari pengalaman negara lain.
Di situlah saya mulai khawatir: kalau di kampus—tempat nalar seharusnya jernih—perdebatan bisa sedangkalan komentar netizen, bagaimana di ruang publik biasa?
Yang kita hadapi bukan defisit energi, tapi defisit kecerdasan publik. Sebagian masyarakat lebih percaya pada meme ketimbang data; lebih cepat menilai orang ketimbang membaca angka. Kritik yang seharusnya tajam malah berubah jadi serangan personal.
Padahal, di negara dengan rasionalitas publik yang sehat, kebijakan seperti ini akan diperdebatkan secara ilmiah: berapa potensi pengurangan impor, berapa efisiensi energi, bagaimana efeknya ke sektor pertanian—bukan siapa yang bicara atau dari suku apa dia berasal.
Indonesia butuh ruang publik yang cerdas, bukan gaduh. Butuh kampus yang bisa jadi tempat belajar logika kebijakan, bukan panggung buzzer intelektual. Karena kalau setiap gagasan baik langsung dipukul dengan sentimen, kapan bangsa ini bisa berinovasi?
Pak Bahlil hanyalah simbol; yang ia bawa adalah arah kebijakan menuju energi bersih dan kemandirian ekonomi. Tapi bagaimana publik merespons justru jadi cermin dari mentalitas kita sendiri.
Kita boleh punya kebijakan energi yang canggih, punya roadmap transisi hijau, punya target Net Zero Emission 2060, tapi kalau publiknya masih sibuk memperolok menterinya ketimbang memahami idenya, maka semua itu cuma jadi jargon.
Pada akhirnya, bangsa ini bukan gagal karena kurang minyak, melainkan karena kurang membaca dan sibuk memaki diri sendiri.
Oleh Abdul Hafid Baso
Pengamat Migas
*Judul terinspirasi dari ungkapan Kahlil Gibran
“Action is the blossom of thought, and joy and suffering are its fruits.”