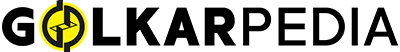Berita Golkar – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa kemunduran kualitas kepemimpinan politik di Indonesia hari ini terkait erat dengan melemahnya fondasi ideologis dalam pembentukan aktor-aktor politik. Hal itu disampaikan dalam acara Ngobras (Ngobrol Santai Ide dan Gagasan) Bareng Bang Idrus Marham bertema “Nomadologi Aktor-aktor Politik Tanpa Ideologi”, yang digelar di Mattea Social Space, Blok M, Selasa (18/11/2025).
Acara ini diselenggarakan Banyan Digital Kreativa bersama Radaraktual.com, Politiknesia.com, dan Rakyatmenilai.com sebagai media partner. Forum ini menghadirkan dialog terbuka yang diikuti mahasiswa, pegiat literasi, aktivis, hingga para politikus muda. Turut hadir sebagai pembicara Dina Hidayana, akademisi yang dikenal dengan analisis politik dari perspektif ketahanan pangan dan Syahmud Basri Ngabalin, pengamat politik dan kebijakan publik. Acara ini dipandu pegiat media sosial yang juga founder Banyan Digital Kreativa, Achmad Annama.
Dalam pemaparannya, Idrus Marham membuka diskusi dengan menekankan pentingnya ruang-ruang intelektual seperti Ngobras untuk menghadirkan kembali perdebatan ideologis di tengah dinamika politik nasional yang semakin pragmatis. Ia menilai forum gagasan sudah terlalu lama ditinggalkan oleh politisi dan publik.
“Saya beri dukungan sepenuhnya kalau acara seperti ini diadakan secara rutin. Pikiran dan ideologi harus tetap menginspirasi gerakan-gerakan yang kita lakukan. Ideologi itu pedoman, ia mengarahkan cara kita berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam politik,” ujar Idrus.
Menurut Ketua Umum IKA UIN Alauddin Makassar ini, krisis kepemimpinan hari ini muncul karena banyak aktor politik melompat tahapan yang seharusnya membentuk kedewasaan berpikir dan karakter seorang pemimpin. Idrus menegaskan bahwa seorang pemimpin ideal lahir dari proses perjuangan panjang yang menuntut kemampuan berpikir, ketahanan mental, kepekaan terhadap persoalan rakyat, dan keteguhan nilai.
“Semua pemimpin itu harus melalui proses perjuangan. Tapi faktanya hari ini, terlalu banyak figur yang ikut-ikutan, tiba-tiba muncul sebagai pemimpin tanpa pernah menjadi pemikir. Dalam kondisi seperti ini, mencari pemimpin yang benar-benar produktif itu sangat sulit,” tegasnya.
Idrus kemudian menguraikan bahwa pemimpin yang memiliki sensitivitas sosial hanya lahir dari pengalaman nyata di lapangan. Tanpa pengalaman itu, seorang pemimpin tidak akan memiliki kepekaan terhadap problem rakyat dan tidak mampu merespons persoalan secara bijaksana.
“Menemukan pemimpin yang sensitif tidak mungkin kalau ia tidak pernah mengalami proses panjang. Sensitivitas itu tumbuh dari pengalaman dan pergulatan, bukan dari pencitraan,” ujar Idrus.
Dalam konteks sistem politik modern, Idrus mengkritik keras pola rekrutmen pemimpin yang menurutnya lebih mengandalkan pertimbangan psiko-sosial politik ketimbang rasionalitas politik. Ia menyebut bahwa masyarakat kini cenderung memilih berdasarkan narasi emosional, terutama narasi dizalimi, ketimbang menilai kapasitas, rekam jejak, dan kompetensi calon pemimpin.
“Strategi politik hari ini dibangun di atas pertimbangan psiko-sosial politik. Kata kuncinya adalah ‘dizalimi’. Untuk dipilih, seseorang tidak harus pintar atau kompeten. Cukup buat skenario bahwa kita dizalimi, dan orang akan merasa kasihan. Kita memilih pemimpin bukan karena kecerdasannya, tapi karena rasa iba,” jelas Idrus.
Ia mengingatkan bahwa pola seperti itu berbahaya karena menempatkan kompetensi di posisi belakang. Dalam jangka panjang, hal tersebut berpotensi merusak kualitas pemerintahan, kebijakan publik, dan perkembangan bangsa.
“Inilah sebabnya Indonesia sulit maju. Kompetensi tidak seimbang dengan posisi yang diduduki. Ketika banyak pemimpin tidak dibentuk oleh proses, tidak diperkaya oleh pemikiran, dan tidak dibimbing oleh ideologi, maka produktivitas tidak mungkin tercapai,” katanya.
Lebih jauh, Idrus menilai bahwa fenomena nomadologi aktor politik, yakni perpindahan sikap, orientasi, dan posisi politik tanpa akar ideologis sedang tumbuh subur. Hal ini membuat politik kehilangan stabilitas nilai dan mengaburkan garis pemikiran antar kelompok.
“Nomadologi ini menciptakan politik yang bergerak tanpa arah ideologis. Aktor-aktor politik berpindah, berubah, dan beradaptasi hanya untuk kepentingan pragmatis. Padahal ideologi seharusnya menjadi jangkar pemikiran, bukan aksesori,” tambah Idrus.
Idrus lantas menegaskan kembali bahwa tanpa fondasi ideologi, mustahil Indonesia mampu menciptakan pemimpin yang kuat, sensitif terhadap persoalan rakyat, dan produktif dalam menghadapi tantangan zaman. Ia mendorong semua pihak, khususnya generasi muda, untuk kembali mengutamakan perdebatan gagasan sebagai inti dari pembangunan politik nasional.