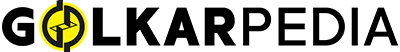Berita Golkar – Podcast Bahlil Lahadalia, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Ketua Umum Partai Golongan Karya, di kanal Youtube Kementerian ESDM kembali viral. Topiknya respons Bahlil terhadap meme dirinya yang membanjiri media sosial dalam beberapa waktu terakhir.
Bahkan, meme tersebut sampai hari ini masih bertambah. Meme merupakan respons publik seiring dengan kebijakan demi kebijakan yang dikeluarkan oleh Bahlil sebagai salah satu menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Mulai dari kebijakan tata kelola distribusi LPG 3 KG, kebijakan tidak menambah kuota impor BBM bagi SPBU swasta hingga penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera yang menyebabkan rusaknya jaringan listrik dan terhambatnya pasokan BBM dan LPG.
Dalam lanskap demokrasi, mengekspresikan unek-unek, kegelisahan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah menggunakan medium meme merupakan hal lumrah. Setiap generasi mempunyai caranya tersendiri untuk berpendapat dan berekspresi.
Mungkin, meme di ruang-ruang digital saat ini mirip dengan selembaran pamflet perlawanan dan surat kabar yang menjadi medium penyebaran ide-ide perjuangan pada masa lalu.
Meme punya dimensi berbeda: kritik berbalut jenaka bernuansa menertawakan keadaan. Namun, dalam konteks meme Bahlil, aksen kritik tertutupi dengan tendensi body shaming yang bias rasial. Jatuhnya bukan lagi kritik, melainkan kebencian yang problematik yang berakar pada konstruksi rasial panjang negeri ini.
Sebagai bangsa, kita harus mengakui belum selesai dengan perbedaan warna kulit dan letak geografis. Stereotipe Jawa dan luar Jawa serta Indonesia Timur masih menghantui memori kolektif kita. Timur masih dikonstruksi dalam benak sebagian masyarakat Indonesia sebagai ‘terbelakang’, ‘keras’ dan ‘tak rupawan’.
Dan ini tercermin dalam meme-meme Bahlil yang bertebaran di media sosial, yang alih-alih menyasar kebijakan sebagai objek kritik, justru terjebak dalam lingkaran setan rasialisme yang tak berkesudahan. Objek kritik netizen tak lagi kebijakan Bahlil, melainkan tubuh Bahlil an sich.
Meme-meme Bahlil yang dibuat oleh sebagian netizen tersebut melanggengkan lingkaran setan rasialisme. Menariknya, respons Bahlil terhadap para pembuat meme-meme dirinya tidak reaksioner: memaafkan.
Bahkan, Bahlil meminta kepada organisasi kepemudaan Partai Golkar seperti AMPI dan AMPG agar tidak melanjutkan pelaporan akun media sosial ke polisi. Tidak sekadar memaafkan, Bahlil menyatakan bahwa meme dirinya yang beredar di publik merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi, di mana para pejabat publik harus terbuka menerima masukan dan kritik publik.
Respons Bahlil yang legowo dan berlapang dada tersebut merupakan wujud kedewasaan elite politik yang patut kita apresiasi karena berkontribusi pada ketahanan demokrasi kita.
Elite politik dan ketahanan demokrasi
Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku How Democracy Die menyatakan bahwa demokrasi mati bukan karena pemimpin diktator, melainkan di tangan pemimpin yang terpilih melalui pemilihan umum. Dalam konteks ini, perilaku para elite politik memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan demokrasi.
Di Indonesia, terdapat banyak elite politik, baik di tingkat nasional maupun daerah, memiliki karakter ‘tipis kuping’ yang memperkarakan secara hukum pelbagai kritik terhadapnya dengan dalih pencemaran nama baik dan penghinaan. Bahkan, sebagian pengkritik tersebut berujung ke bui.
Memang, kritik bisa ditafsiri dengan luwes sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik karena dianggap serangan terhadap sosok elite politik. Mengkritik kebijakannya dianggap menghina kehormatannya sebagai pejabat publik.
Padahal, jika elite politik kita memiliki kesadaran dan kedewasaan politik terkait perbedaan yang-publik dan yang-privat, pelbagai pelaporan dengan dalih penghinaan dan pencemaran nama baik tidak akan terjadi. Jika pelaporan demi pelaporan oleh para elite politik tersebut terus terjadi, maka ketahanan demokrasi kita menjadi taruhannya.
Djayadi Hanan dalam Opini Harian Kompas (22/8/2025) mengemukakan dua sumber ketahanan demokrasi, yaitu kepercayaan publik dan komitmen elite terhadap demokrasi, yang diejawantahkan ke dalam sikap dan perilaku keseharian berbangsa-bernegera.
Dengan kata lain, demokrasi bisa bertahan jika publik dan elite memiliki komitmen tinggi dan sikap positif terhadap demokrasi. Apa yang dilakukan oleh Bahlil dengan memaafkan para pembuat meme dirinya merupakan salah satu perilaku elite politik yang positif terhadap ketahanan demokrasi.
Ketika memegang jabatan publik dan posisi politik dalam genggamannya, mudah saja bagi seseorang Bahlil untuk memperkarakan secara hukum akun-akun media sosial pembuat meme dirinya tersebut, sebagaimana dilakukan oleh banyak elite politik negeri ini. Namun, Bahlil memilih jalan demokratik yang patrotik: memaafkan.
Bahkan Bahlil menanggapinya dengan tertawa sembari berseloroh “om suka, om suka”. Komitmen dan sikap Bahlil tersebut merupakan akumulasi dari pengalaman hidupnya yang panjang, yang berangkat dari kampung, bukan anak pejabat, menjadi aktivis, lalu pengusaha dan kini pejabat publik serta ketua umum partai politik.
Bahlil mungkin sudah kebal dengan hal-hal yang lebih pahit dan menyakitkan dalam hidup ketimbang hinaan, makian dan cemohan orang. Berkat sistem demokrasi lah, jalan Bahlil menjadi elite politik di negeri ini terbuka. Karena itu, Bahlil tidak mau mengikis ketahanan demokrasi hanya karena soal meme-meme dirinya.
Kedewasaan dan kelapangdadaan elite politik –termasuk dewasa dan legowo terhadap hate speech, cemohon dan hinaan yang bias rasial dan mengarah pada perilaku body shaming– merupakan sumber penting ketahanan demokrasi kita.
Semakin banyak elite politik seperti Bahlil yang merespons ‘kritik’ dengan tidak melaporkan ke ranah hukum, maka semakin kokohlah ketahanan demokrasi kita. Elite politik di negeri ini sudah seharusnya mempunyai kesadaraan dan kedewasaan politik yang demikian. {Kompas}
Oleh: Melfin Zaenuri, Direktur Eksekutif The Strategic Lab | Alumnus Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta, Alumnus Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia