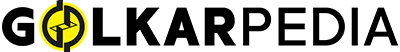Berita Golkar – Kesenjangan antara desa dan kota saat ini masih menjadi luka terbuka dalam pembangunan Indonesia. Kemiskinan di desa bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan distribusi hasil pembangunan.
Dalam kajian terbaru, pakar hukum dan politik Prof. Dr. Henry Indraguna, SH, MH, menyerukan pengembalian roh pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi konstitusional untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di desa.
“Ini menjadi kunci membuka jalan konstitusional untuk keadilan dan pemerataan kesejahteraan yang sejati di usia 80 tahun Indonesia ini,” ujar Prof Henry kepada suarakarya.id memaknai 80 tahun Kemerdekaan RI, di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, ditemukan 12,2% penduduk desa hidup di bawah garis kemiskinan. Angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata warga di perkotaan dan masyarakat urban.
Ironisnya lagi ketimpangan ini diperparah oleh terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan modal usaha. “Desa bukan hanya tertinggal. Akan tetapi juga dijadikan objek eksploitasi, bukan subjek pembangunan,” bebernya.
Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini juga menyoroti dominasi dan eksploitasi berlebihan dari korporasi besar atas sumber daya alam seperti tanah, tambang, energi, dan hutan maupun pertanian dan perkebunan yang kerap kali tidak memberikan manfaat nyata bagi warga setempat.
Sementara itu, pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, maupun bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, justru jauh saat sekarang yang terjadi selama 80 tahun usia republik jauh dari harapan pendiri bangsa.
Profesor dan Guru Besar Unissula Semarang ini menyesalkan peran negara yang kini lebih sebagai regulator pasif, bukan pelaku aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Lalu, bagaimana cara mengembalikan pasal 33 sebagai jalan konstitusional menuju pemerataan?
Prof Henry mengusulkan sejumlah langkah strategis. Pertama adalah jebijakan ekonomi nasional harus direorientasi dengan menjadikan pasal 33 sebagai hukum ekonomi tertinggi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), undang-undang, dan kebijakan fiskal.
“Ini tak boleh hanya sekadar wacana, tetapi keharusan atau mandatori konstitusional yang ditaati dan dijalankan secara sungguh-sungguh dan konsisten oleh segenap tumpah darah Indonesia,” tegas Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini.
Kedua, dia mendorong upaya penuh pemberdayaan ekonomi desa melalui revitalisasi koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Prof Henry mempertegas koperasi adalah soko guru ekonomi rakyat yang lahir dari usaha dan peluh rakyat yang lebih murni memberikan penghidupan ekonomi kepada rakyat itu sendiri karena penguasaannya secara kolektif dan gotong-royong atau tidak ada yang bersifat menjadi mayoritas maupun monopoli tunggal.
“Namun sayangnya selama ini yang terjadi dalam tataran praksis justru keberadaan koperasi dibiarkan melemah. Untuk itu BUMDes juga perlu dilakukan pendampingan teknokratik dan dukungan modal agar bisa mengelola potensi lokal, seperti sumber daya alam dan pariwisata,” terangnya.
Undang-Undang Ekonomi Kerakyatan dan Reforma Desa Berkeadilan
Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menunjukkan bahwa hingga 2024, hanya 20% dari 75 ribu BUMDes yang benar-benar aktif dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian desa.
Lebih lanjut Prof Henry menjabarkan
langkah strategis berikutnya adalah pentingnya reforma agraria dan redistribusi akses terhadap sumber daya alam (SDA).
Tanah dan sumber daya alam harus dikelola secara kolektif oleh warga desa atau warga lokal yang memiliki hubungan emosional dan kesejarahan dengan porsi yang seimbang dengan pengelolaan dari swasta, BUMN maupun BUMD di sumber daya alam tersebut berada dan bukan dikuasai oleh korporasi besar.
“Selama ini ada monopoli yang terjadi di sektor pertambangan dan kehutanan, yang sering kali hanya menyisakan kerusakan lingkungan bagi masyarakat lokal,” ungkap Ketua DPP Ormas MKGR ini.
Prof Henry lalu mencontohkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2023 yang menyebutkan bahwa lebih dari 60% konsesi hutan di Indonesia dikuasai segelintir perusahaan besar, sementara masyarakat adat dan desa sekitar minim mendapat manfaat.
Untuk itu, Prof Henry memberiksn masukan keempat yakni perlunya legislasi pro-rakyat desa. Karenanya sangat penting dilakukan pembentukan Undang-Undang Ekonomi Kerakyatan dan Undang-Undang Reforma Desa Berkeadilan yang berpijak pada esensi pasal 33.
“UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 sudah baik. Tetapi implementasinya harus selaras dengan prinsip ekonomi kekeluargaan dan kemandirian lokal,” tandasnya.
Waketum DPP Bapera sekaligus Ketua LBH DPP Bapera ini pun menyinggung perlunya penegakan hukum yang tegas untuk mencegah eksploitasi sumber daya desa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hayati.
Kembali dia menegaskan bahwa mengembalikan pasal 33 UUD 1945 bukanlah sekadar retorika, melainkan langkah nyata untuk mewujudkan keadilan sosial.
“Desa adalah wajah mayoritas Indonesia. Jika desa sejahtera, maka Indonesia akan kuat, tangguh, dan memiliki daya saing tinggi,” tegas Ketua Dewan Penasehat DPP AMPI ini.
Maka pendekatan yang mengedepankan kolektivitas, pemberdayaan, dan keadilan diyakini mampu menekan angka kemiskinan di desa bahkan menghapusnya.
“Seorang filsuf Amerika Latin, Paulo Freire, pernah mengatakan bahwa tidak ada perubahan sejati tanpa membebaskan mereka yang tertindas,” ucap Prof Henry meminjam kata bijak filsuf dunia.
Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini akan terus mendorong dan mengkampanyekan bahwa kekuatan desa harus menjadi subjek pembebasan, bukan sekadar penonton dalam pembangunan.