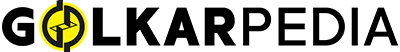Berita Golkar – Pada awal 2025, dunia menyaksikan kembalinya Donald J. Trump ke Gedung Putih. Hanya beberapa pekan setelah pelantikannya, kebijakan tarifnya kembali mengguncang sistem perdagangan dunia. Trump menetapkan tarif baru sebesar 60% terhadap impor dari Tiongkok dan rata-rata 40% terhadap sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia yang terkena 32%.
Sejak itu, respons keras berdatangan: Tiongkok membalas dengan embargo bahan baku industri teknologi, Uni Eropa menetapkan tarif balasan, dan India memberlakukan pembatasan investasi dari AS. Kita tidak sedang berbicara tentang sekadar perang tarif, tetapi tentang pecahnya blokade geoekonomi global.
Dunia kembali terbelah: di satu sisi, blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dengan jaringan IPEF, AUKUS, dan G7; di sisi lain, blok Tiongkok – Rusia yang merajut kekuatan melalui BRICS+, Belt and Road Initiative, dan mata uang alternatif non-dollar. Inilah babak baru dari sejarah hubungan internasional—bukan Perang Dingin kedua, tetapi sesuatu yang lebih cair, lebih kompleks, dan mungkin lebih berbahaya.
Dari Perdagangan ke Pertarungan Dominasi
Teori geoekonomi, sebagaimana dipopulerkan oleh Blackwill dan Harris (2016), menyatakan bahwa negara kini menggunakan alat ekonomi – bukan hanya militer – untuk memaksakan kepentingannya. Apa yang kita lihat hari ini adalah realisasi dari teori tersebut: tarif dijadikan alat tekanan, investasi dijadikan senjata diplomasi, dan rantai pasok global dijadikan instrumen subordinasi.
Bank Dunia dalam laporan terbarunya (Global Economic Outlook Q1 2025) menyebut bahwa eskalasi perang tarif telah menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi global menjadi hanya 1,6%, terendah sejak krisis keuangan 2008. Biaya logistik melonjak 28%, harga pangan dunia naik 14%, dan inflasi global kembali menembus 7%.
Tarif-tarif baru bukan hanya memukul Tiongkok dan Rusia, tapi juga menekan negara berkembang seperti Indonesia. Industri manufaktur kita terguncang. Ekspor produk nikel olahan, tekstil, dan elektronik mengalami penurunan hingga 23% dalam kuartal pertama 2025. Strategi friendshoring yang diterapkan AS – memindahkan rantai pasok ke negara “ramah” – justru mempersempit ruang gerak negara yang mengambil posisi netral.
Geopolitik dalam Format Baru: Blok vs. Blok
Jika dulu Perang Dingin memisahkan dunia berdasarkan ideologi, hari ini pemisahan itu terjadi atas dasar kepentingan dagang, kendali teknologi, dan dominasi energi. Tanpa disadari, dunia semakin bergerak menuju formasi geopolitik baru yang berhadap-hadapan secara struktural.
Di satu sisi, ada Blok Barat yang terdiri dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Australia, dan sekutu NATO lainnya. Blok ini fokus pada penguatan standar lingkungan, hak asasi manusia, dan pengembangan teknologi tinggi yang berbasis nilai-nilai liberal. Di sisi lain, ada Blok Timur-Selatan, yang mencakup Tiongkok, Rusia, Iran, Brasil, dan sebagian besar negara Global South. Blok ini menekankan pentingnya keterhubungan infrastruktur, kedaulatan ekonomi, dan kerja sama berbasis interdependensi material.
Indonesia kini berada di tengah tekanan kedua kutub ini. Di satu sisi, Indonesia tetap berkomitmen pada ASEAN, IPEF, dan kemitraan Indo-Pasifik, sementara di sisi lain, negara ini memiliki peluang besar dalam BRICS+, Belt and Road Initiative (BRI), serta kerja sama Selatan-Selatan.
Diplomasi dagang Indonesia kini diuji, dan pilihan untuk tetap netral tidak lagi bisa dianggap netral jika tidak disertai dengan keberanian strategis yang jelas.
Apakah Ini Prolog Perang Dunia Ketiga?
Pertanyaan ini tak bisa dijawab dengan spekulasi, tetapi harus disikapi dengan kesadaran sejarah. Dua Perang Dunia terdahulu tidak langsung diawali oleh konflik bersenjata besar, melainkan dimulai dengan eskalasi blok, nasionalisme ekonomi, dan kebuntuan diplomasi. Perang dagang sering kali menjadi pemicu dari ketegangan yang lebih besar.
Pada awal abad ke-20, misalnya, meningkatnya proteksionisme dan kebijakan tarif tinggi di Eropa dan Amerika Serikat berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi global, yang akhirnya memunculkan ketegangan politik yang meluas. Dalam konteks saat ini, kita melihat gejala yang serupa mulai muncul. Ketegangan di Selat Taiwan meningkat pasca latihan militer Tiongkok yang mengepung pulau tersebut selama seminggu penuh pada Agustus 2024, yang melibatkan lebih dari 100 pesawat tempur dan 10 kapal perang.
Sementara itu, konflik Rusia-Ukraina terus meluas, dengan dampak yang terlihat di negara-negara sekitar, seperti Moldavia dan Laut Hitam, yang mengalami peningkatan ketegangan militer, dengan hampir 14.000 korban jiwa tercatat sejak invasi Rusia dimulai pada Februari 2022.
Selain itu, titik nyala baru juga muncul di Timur Tengah dan Asia Selatan, dari Gaza hingga Kashmir, dengan risiko eskalasi yang tinggi. Dalam beberapa bulan terakhir, pertempuran antara Israel dan kelompok Hamas di Gaza meningkat tajam, menewaskan lebih dari 3.000 orang pada tahun 2024 saja.
Di sisi lain, ketegangan di Kashmir antara India dan Pakistan juga semakin memuncak, dengan India melaporkan lebih dari 1.000 bentrokan militer di wilayah tersebut pada tahun 2024. Organisasi think-tank Eropa, International Crisis Group, bahkan telah mengeluarkan peringatan bahwa konflik-konflik regional ini dapat berkembang menjadi konflik multiblok dalam skenario terburuk, jika Amerika Serikat dan Tiongkok terseret dalam konfrontasi terbuka.
Ini semakin mungkin terjadi mengingat keterlibatan AS dan Tiongkok dalam persaingan global yang semakin intens, yang dipicu oleh kebijakan tarif, persaingan teknologi, dan kontrol terhadap jalur perdagangan strategis.
Apa Peran Indonesia?
Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, dan sekaligus mitra dagang penting baik untuk Tiongkok maupun AS, Indonesia memiliki posisi tawar yang sangat strategis dalam peta geopolitik global. Nikel, yang merupakan bahan utama dalam produksi baterai kendaraan listrik dan berbagai produk teknologi lainnya, menjadi komoditas yang sangat dicari di pasar internasional.
Pada 2023, Indonesia menyuplai sekitar 30% dari kebutuhan nikel dunia, dengan sebagian besar diekspor ke Tiongkok dan sejumlah negara lainnya. Selain itu, Indonesia juga memiliki hubungan dagang yang kuat dengan AS, terutama dalam sektor energi, pertanian, dan manufaktur.
Namun, kekuatan ekonomi ini hanya akan berarti jika Indonesia mampu mengintegrasikan beberapa elemen kunci dalam kebijakan nasionalnya. Pertama, Indonesia perlu memiliki grand strategy nasional yang menghubungkan diplomasi luar negeri dengan transformasi industri dalam negeri.
Transformasi ini mencakup peningkatan nilai tambah pada komoditas mineral seperti nikel, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan dan teknologi. Dalam hal ini, Indonesia harus mampu memanfaatkan sumber daya alamnya untuk mendorong kemajuan ekonomi domestik sambil memperkuat posisi tawar di arena global.
Kedua, Indonesia harus mencapai kemandirian logistik dan energi agar tidak terjebak dalam potensi embargo geopolitik yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan yang tinggi pada impor energi dan bahan bakar fosil dari negara-negara besar bisa menjadi titik lemah dalam ketahanan ekonomi Indonesia, terlebih dengan meningkatnya ketegangan internasional. Untuk itu, pengembangan infrastruktur energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi, serta diversifikasi sumber energi menjadi prioritas utama.
Ketiga, Indonesia perlu menjalankan diplomasi aktif multi-poros, bukan hanya mengandalkan netralitas pasif. Diplomasi Indonesia di era globalisasi harus lebih proaktif dalam membangun aliansi strategis, tidak hanya di tingkat regional melalui ASEAN, tetapi juga di tingkat global melalui forum-forum seperti G20 dan PBB.
Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat berperan sebagai penyeimbang regional yang tidak hanya mengamati, tetapi juga aktif terlibat dalam meredakan ketegangan internasional, serta menjadi juru damai global. Peran semacam ini pernah Indonesia mainkan dengan sukses pada masa Konferensi Asia Afrika 1955, di mana Indonesia berhasil memperjuangkan kemerdekaan negara-negara berkembang dan menegaskan kedaulatan negara-negara baru yang baru saja merdeka. Dalam konteks dunia yang semakin terfragmentasi, Indonesia memiliki potensi untuk memainkan kembali peran tersebut dengan pendekatan yang lebih modern dan relevan.
Implementasi Asta Cita
Sebagai catatan, semua elemen strategis tersebut sejatinya telah termaktub dalam AstaCita – delapan agenda visi, misi, dan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Dokumen tersebut menekankan pentingnya hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, ketahanan energi nasional, serta peningkatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global melalui diplomasi ekonomi yang aktif.
Asta Cita juga menegaskan komitmen terhadap pembangunan pertahanan dan kemandirian logistik sebagai fondasi bagi kedaulatan bangsa. Visi ini, di atas kertas, mencerminkan pemahaman yang tepat terhadap tantangan geopolitik dan geoekonomi yang sedang berlangsung, serta tekad untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju berbasis kekuatan nasional yang menyeluruh.
Namun demikian, pertanyaannya bukan semata pada tingkat perencanaan, melainkan pada presisi dan konsistensi realisasi.
Apakah semua rencana besar itu bisa dijalankan secara sinkron antar kementerian?
Apakah birokrasi siap bertransformasi dalam tempo yang cukup cepat untuk merespons dinamika global yang semakin tidak menentu?
Realisasi visi besar seperti AstaCita membutuhkan tata kelola yang disiplin, kapasitas fiskal yang kokoh, serta keberanian politik untuk mengambil keputusan strategis yang kadang tidak populer. Sebab dalam situasi internasional yang penuh ketegangan dan kompetisi, ketertinggalan bukan hanya soal kehilangan peluang, tetapi bisa berarti kehilangan kedaulatan. Maka dari itu, ke depan, tantangan terbesar bukan lagi pada perumusan gagasan, melainkan pada pelaksanaan secara
Pada akhirnya, perang dagang 2025 adalah lebih dari sekadar angka ekspor-impor. Ia adalah simbol dari pecahnya konsensus global dan terbentuknya tatanan baru yang belum tentu lebih aman. Dunia yang terbelah adalah dunia yang rapuh. Dan jika percikan konflik ekonomi tak diredam dengan diplomasi, maka bukan tak mungkin, sejarah akan kembali menulis babak kelamnya.
Kita belum tentu menuju Perang Dunia Ketiga, tapi kita jelas sedang berjalan di tepi jurangnya. Maka diplomasi, keberanian, dan ketegasan visi adalah kunci agar Indonesia tidak jatuh – melainkan justru naik panggung sebagai kekuatan penengah dunia yang baru.
Novianty
Sekretaris Jenderal PP KPPG