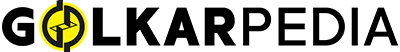Berita Golkar – Perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah kembali mengemuka. Di tengah evaluasi atas mahalnya biaya politik, maraknya politik uang, serta polarisasi sosial yang berulang dalam setiap pilkada langsung, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali dipersoalkan. Sebagian pihak langsung melabelinya sebagai kemunduran demokrasi. Padahal, jika ditelaah secara jernih, anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat.
Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak pernah memerintahkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota “dipilih secara demokratis”. Frasa ini sengaja dirumuskan terbuka oleh para penyusun konstitusi, agar mekanisme pemilihan dapat disesuaikan dengan perkembangan demokrasi dan kebutuhan bangsa.
Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya juga menegaskan bahwa pemilihan oleh DPRD tidak bertentangan dengan konstitusi. Selama DPRD dipilih melalui pemilu yang sah, dan proses pemilihan kepala daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, serta kompetitif, maka prinsip demokrasi tetap terpenuhi. Dengan demikian, persoalan pilkada oleh DPRD bukanlah persoalan konstitusional, melainkan pilihan desain sistem politik.
Demokrasi modern tidak identik dengan pemilihan langsung dalam setiap level pemerintahan. Banyak negara demokrasi mapan justru mengandalkan mekanisme perwakilan untuk memilih kepala pemerintahan daerah. Di Jerman, misalnya, kepala pemerintahan negara bagian (Ministerpräsident) dipilih oleh parlemen negara bagian (Landtag). Sistem ini melahirkan stabilitas pemerintahan, disiplin koalisi, dan akuntabilitas kebijakan yang kuat.
Inggris juga menerapkan mekanisme serupa. Di banyak daerah, kepala pemerintahan lokal (council leader) tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan oleh anggota dewan lokal. Model ini menekan biaya politik, memperkuat peran parlemen daerah, dan meminimalkan konflik sosial akibat kontestasi elektoral. Negara-negara tersebut tetap diakui sebagai demokrasi berkualitas tinggi.
Pengalaman internasional ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak diukur dari seberapa sering rakyat mencoblos, melainkan dari seberapa efektif sistem pemerintahan bekerja untuk kepentingan publik. Demokrasi adalah soal substansi, bukan semata prosedur.
Dalam konteks Indonesia, pilkada langsung memang memberi ruang partisipasi rakyat yang luas. Namun, praktik selama hampir dua dekade juga menunjukkan persoalan serius. Biaya politik yang sangat tinggi mendorong banyak kepala daerah terjerat korupsi. Politik identitas kerap dimobilisasi, meninggalkan luka sosial yang tidak mudah dipulihkan. Kemampuan masyarakat secara umum untuk menentukan pilihan secara substansi, bukan hanya popularitas semata. Pada saat yang sama, kualitas kepemimpinan daerah tidak selalu berbanding lurus dengan mahalnya ongkos demokrasi yang dibayar negara dan masyarakat.
Pemilihan kepala daerah oleh DPRD menawarkan alternatif yang patut dipertimbangkan. Pertama, mekanisme ini dapat menekan biaya politik secara signifikan. Kontestasi berpindah dari ruang publik yang penuh mobilisasi emosional ke ruang institusional yang lebih terkontrol. Kedua, relasi antara kepala daerah dan DPRD menjadi lebih seimbang, karena DPRD tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga ikut bertanggung jawab atas kepemimpinan yang dipilihnya. Ketiga, potensi polarisasi sosial dapat diminimalkan karena kompetisi tidak lagi langsung melibatkan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.
Tentu saja, pemilihan oleh DPRD bukan tanpa risiko. Politik transaksional di parlemen daerah harus diantisipasi dengan desain hukum yang ketat, transparansi proses, keterlibatan publik, serta penguatan etika dan penegakan hukum. Namun, risiko ini tidak lebih besar dibandingkan problem yang selama ini muncul dalam pilkada langsung.
Penting ditegaskan, selama Undang-Undang Pilkada masih mengatur pemilihan langsung oleh rakyat, maka mekanisme tersebut tetap berlaku dan mengikat. Perubahan sistem hanya dapat dilakukan melalui revisi undang-undang oleh DPR dan Presiden. Oleh karena itu, perdebatan ini seharusnya diarahkan pada diskursus kebijakan publik yang rasional, bukan pada stigma seolah-olah pilihan selain pilkada langsung adalah anti-demokrasi.
Pada akhirnya, demokrasi adalah sarana, bukan tujuan. Tujuannya adalah menghadirkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Jika pemilihan oleh DPRD dapat dirancang secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, maka mekanisme tersebut tetap berada dalam koridor demokrasi dan konstitusi.
Pertanyaannya bukan lagi “langsung atau tidak langsung”, melainkan: sistem mana yang paling mampu menjawab tantangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Indonesia hari ini.
Maju Terus! Pantang Mundur!
Oleh Abrory Ben Barka
Ketua Umum Bakornas Fokusmaker