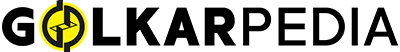Berita Golkar – Di dalam gedung parlemen yang dingin dan penuh formalitas di Senayan, suara lantang seorang Perempuan menggema. Ranny Fahd Arafiq, Anggota Komisi IX DPR RI menyuarakan kegelisahan publik dalam rapat yang membahas sesuatu yang seharusnya tak pernah terjadi di negeri ini dugaan malpraktik dalam pelayanan kesehatan.
Tapi di balik suara dan data, ia bukan hanya berbicara sebagai legislator, melainkan sebagai manusia yang mewakili jutaan jeritan sunyi dari ranjang- ranjang rumah sakit yang terdengar oleh birokrasi, ucapnya di Jakarta pada Sabtu.(5/7/2025)
Dalam ruangan dimana teori kedokteran dipertemukan dengan politik kebijakan, Ranny tak hanya menuntut jawaban. Ia menuntut jiwa dari sistem yang terlalu lama mengandalkan prosedur, namun kehilangan hati.
Baginya persoalan malpraktik bukan hanya persoalan teknis, tapi cerminan dari retaknya relasi antara etika dan kekuasaan. Apakah kita masih memiliki rasa hormat terhadap nyawa manusia? Ataukah semuanya telah menjadi statistik dalam laporan Kementerian?
Hal ini bukan sekedar sebagai pertarungan antara dokter dan pasien, atau antara DPR dan Kemenkes. Ini adalah dialektika eksistensial antara profesionalisme dan kemanusiaan. Dimana, pada satu titik, keahlian tak lagi memadai bila tak disertai welas asih. Dimana seragam putih menjadi symbol bukan hanya kompetisi, tetapi juga moralitas. Namun hari ini, simbol itu tampak mulai kehilangan makna.
Indonesia, negeri dengan ribuan puskesmas dan rumah sakit, seolah lupa bahwa setiap layanan Kesehatan adalah perjumpaan antara harapan dan ketakutan. Bahwa setiap pasien bukan hanya objek penyembuhan, tapi subjek yang membawa kisah, trauma dan harapan untuk hidup lebih baik. Tapi apa jadinya jika ruang yang seharusnya menyembuhkan justru menjadi ruang yang mencederai?
Ranny menyampaikan bahwa laporan masyarakat tentang dugaan malpraktik bukan lagi kasus terisolasi. Ini adalah gejala sistemik. Dan gejala itu ibarat tumor yang tak terlihat dari permukaan, namun secara diam-diam menyebar dan merusak jaringan kepercayaan antara rakyat dan Lembaga layanan Kesehatan. “kita harus bedah system ini.” Tegasnya. Tetapi siapa yang berani memegang pisau bedah terhadap tubuh institusi yang terlalu lama nyama dalam zona aman?
Pertemuan dengan IDI, IBI dan PPNI seharusnya menjadi ruang otokritik. Namun, seperti dalam banyak forum formal, kejujuran seringkali kalah oleh diplomasi. Padahal, saat kejujuran hilang, keadilan ikut terkubur. Dan Ketika keadilan mati, sistem kesehatan berubah dari tempat penyembuhan menjadi ladang kekuasaan teknokratik yang sunyi dari nurani.
Plato pernah menyebutkan bahwa keadilan hanya mungkin hadir jika setiap bagian dari tubuh masyarakat menjalankan fungsinya dengan baik. Tatapi bagaimana jika bagian itu justru menyimpang? Apakan kita akan tetap memberikannya karena takut kehilangan stabilitas semu?
Ranny juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap profesionalisme tenaga kesehatan. Evaluasi bukan bentuk penghukuman, tetapi bentuk cinta terhadap profesi itu sendiri. Seperti seorang guru yang mengevaluasi muridnya, negara harus berani menilai tenaga kesehatannya, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki.
Sayangnya, kritik terhadap tenaga kesehatan seringkali dianggap sebagai serangan terhadap profesi, padahal, kritik yang lahir dari data dan empati justru adalah bentuk tertinggi dari cinta terhadap profesi itu sendir. Hanya mereka yang peduli yang berani menggugat. Hanya mereka yang takut kehilangan martabat profesi yang berani meminta reformasi.
Masalah malpraktik, dalam pengertian metaforis, adalah gejala dari tubuh sosial yang sedang demam. Ia mengindikasikan ada yang salah pada sistem imunitas etika. Dan seperti tubuh yang demam, negara sekedar obat penenang berupa janji birokrasi.
Kita hidup di zaman dimana informasi mudah menyebar, tetapi rasa keadilan justru semakin langka. Di media sosial, kisah-kisah pasien yang merasa dizalimi oleh tenaga kesehatan viral, namun tak pernah benar-benar mendapatkan kepastian hukum. Apakah negara hanya hadir di ruang digital dan bukan diruang-ruang luka nyata?
Dalam sejarah panjang pelayanan kesehatan Indonesia, etika kedokteran dahulu ditulis dengan tinta pengabdian dan dedikasi. Namun hari ini, banyak yang ditulis dengan birokrasi dan laporan administratif yang tak pernah menyentuh substansi. Reformasi yang diminta Ranny bukan hanya soal regulasi, tapi soal mengembalikan etika ketempat asalnya hati.
Bayangkan seorang ibu dari desa yang datang ke RSUD membawa anaknya yang demam tinggi. Ia buta huruf, tak tahu prosedurnya, tak tahu haknya. Ia hanya percaya. Tapi kepercayaan itu bisa musnah dalam sekejap, Ketika pelayanan diterima bukan sebagai manusia, tapi sebagai “kasus berikutnya”. Kita kehilangan rasa hormat terhadap kehidupan itu sendiri.
Reformasi layanan kesehatan yang diminta Ranny bukanlah tugas kecil. Ia seperti merancang kembali mesin besar yang telah berjalan selama puluhan tahun. Tapi seperti arsitek yang baik, kita tak bisa hanya menambal. Kita harus berani membongkar bagian yang rusak, bahkan jika itu berarti mengguncang kenyamanan sebagian orang.
Sebagian pihak mungkin merasa tersinggung, tapi perubahan sejati tak lahir dari kenyamanan. Ia lahir dari ketidaknyamanan, dari desakan nurani yang telah melihat ketidakadilan terus berlangsung. Dan Ranny memilih berdiri di sisi ketidaknyamanan itu, bukan untuk mencela, tapi untuk menyembuhkan.
Komisi IX mendorong penyusunan roadmap etika yang konkret dan terukur. Ini penting. Tapi yang lebih penting lagi apakan roadmap itu disusun oleh mereka yang benar-benar paham luka Masyarakat? Atau oleh mereka yang hanya ingin menenangkan amarah publik sementara?
Manusia selalu berada dalam pertarungan antara otentisitas dan kepalsuan. Begitu juga profesi. Apakah profesi tenaga kesehatan akan tetap otentik melayani demi kemanusiaan? Atau ia akan tergelincir menjadi mesin industry kesehatan yang melupakan wajah manusia?
Penyembuhan terbesar bukan datang dari obat, tapi dari empati. Dokter terbaik bukan hanya yang paling cerdas, tapi yang paling mampu memahami rasa takut dan harapan pasiennya. Sistem terbaik bukan yang paling efisien, tapi yang paling adil.
Jika sistem kesehatan adalah cermin dari peradaban, maka saat ini cermin itu retak. Dan dalam retaknya, kita melihat wajah kita sendiri yang penuh luka, harapan dan kemarahan yang belum tersalurkan. Tapi setiap retakan adalah peluang. Peluang untuk membentuk ruang.
Ranny Fahd Arafiq telah menyalakan api kecil dalam ruang gelap birokrasi kesehatan. Tapi api itu hanya bisa menyala jika kita semua meniupkan keberanian padanya. Masyarakat, pemerintah dan profesi harus berhenti saling menyalahkan, dan mulai saling menyembuhkan. Karena di ujung setiap prosedur, dibalik setiap stetoskop, selalu ada satu hal yang tak boleh dilupakan yaitu nyawa manusia. {}