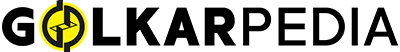Berita Golkar – Perjalanan 27 tahun Reformasi bisa dimaknai berbeda. Itulah yang tercermin dalam talkshow Satu Meja The Forum KompasTV, Rabu malam.
Aktivis 1998 yang kini jadi Gubernur Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional) Ace Hasan Sjadzili mengatakan, jika tidak ada reformasi, tidak mungkin mengantarkan dirinya sebagai orang sipil menjadi orang nomor satu di Lemhannas. Lemhannas adalah “sekolah” calon pemimpin. Selama ini asosiasi Lemhannas adalah militer.
Meski sejumlah pemimpin sipil pernah menjadi Gubernur di sana seperti Andi Widjajanto, Muladi, Ermaya Suryadinata, Budi Susillo Supandji. Dan, terakhir Ace Hasan, politisi Partai Golkar, dikutip dari Kompas.
Argumen Ace masuk akal. Sebelum Reformasi 1998, Gubernur Lemhannas didominasi perwira tinggi militer seperti Agum Gumelar, R Hartono, Moetojib, Agus Widjojo, Johny Lumintang dan Sofian Effendi. Mohammad Qodari, kini Wakil Kepala Kantor Staf Kepresidenan, berpandangan perubahan UUD 1945 sampai empat tahapan adalah hasil dari reformasi.
Perubahan keempat UUD 1945 telah mengembalikan kedaulatan rakyat pada tempat semestinya. Pemilihan Presiden langsung, ada Mahkamah Konstitusi dan sejumlah lembaga demokrasi lain. Reformasi sudah berbuah, dan buahnya masih bisa dilihat sampai hari ini.
Misalnya, kekuasaan yang tak lagi terpusat, melainkan bercabang dan terdistribusi, otonomi daerah, masa jabatan presiden yang dibatasi, partai politik tak lagi tunggal.
Sebaliknya Savic Ali, pengunjuk rasa tahun 1998, yang tetap berada di luar kekuasaan, berkomentar, “Saya menyaksikan bahwa secara umum spirit reformasi sudah menguap, walaupun warisan reformasi masih cukup banyak bisa kita saksikan.”
“Semangat untuk membangun keadilan ekonomi yang dulu dipegang kini tak lagi terlihat dimiliki para elite politik kita. Meskipun, produk hasil reformasi masih bertebaran dan mudah dijumpai di Indonesia,” tambah dia.
Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Usman Hamid yang saat itu merupakan mahasiswa Universitas Trisakti di mana sejumlah kawannya tertembak dalam kerusuhan 1998 mengaku optimistis keadilan akan mewujud di kemudian hari.
Namun 26 tahun berselang, keadilan yang diharapkan tak kunjung mewujud. Keadilan itu bukan hanya belum didapatkan oleh keluarga mahasiswa korban penembakan dalam perjuangan reformasi, tapi juga masyarakat lain dalam kejadian-kejadian pelanggaran HAM berbeda yang terjadi di Indonesia.
“Sampai hari ini sepertinya terlupakan dan pemerintah seperti bukan hanya melupakan, bahkan tidak mengupayakan sama sekali adanya supremasi hukum dan hak asasi manusia seperti yang dulu kita cita-citakan,” sebut Usman.
Ia bahkan heran dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang di hari pertama pemerintahannya justru menyangkal telah terjadi pelanggaran HAM berat di tahun 1998. Di mata Usman, itu sangat menyakitkan bagi keluarga korban yang lama menanti datangnya keadilan.
Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera Bivitri Susanti tak sepenuhnya setuju dengan penjelasan Qodari. Reformasi seharusnya tak hanya dilihat dari sisi insitusional di mana empat amandemen UUD 1945 telah dilakukan. Namun juga substansional.
Secara substansi, reformasi memang nampak baik-baik saja. Indonesia nampak masih demokratis, meski perlahan mulai kembali mengarah ke otoritarianisme. Sementara jika dilihat secara substansi, Bivitri mencontohkan enam tuntutan reformasi yang hampir semuanya tak lagi terpenuhi.
“Amandemen konstitusi itu kan cuma satu (tuntutan), ada lima lagi. Misalnya Adili Soeharto. Sekarang Soeharto malah mau dijadikan pahlawan, padahal dia belum pernah diadili. Kemudian otonomi daerah, betul pasal 18B-nya di konstitusi ada, tapi gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja, sudah balik lagi resentralisasi. Pemberantasan KKN, KPK-nya dibunuh kok lewat undang-undang tahun 2019. Atau penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu (sekarang justru disangkal),” ujarnya.
Intelektual Sukidi Mulyadi menarik refleksi yang lebih filosofis tentang reformasi. Dari sudut pandang pribadinya, api reformasi hari ini telah padam. Api reformasi itu adalah ide besar tentang negara yang bertransisi dari otoriter menjadi demokrasi.
Namun, yang terjadi sekarang adalah sebaliknya. Indonesia sebagai negara demokrasi, sudah tidak benar-benar demokratis. Indonesia secara perlahan mulai bergerak kembali ke model otoritarianisme.
Ilmuwan politik dari Amerika Serikat Prof Steven Levitsky memperkenalkan konsep the weaponized state, negara sebagai senjata politik bagi keberlangsungan pemerintahan otoriter. Ia mencontohkan bukti konkret terjadinya the weaponized state di Indonesia.
“Kita melihat bagaimana hukum dipakai sebagai senjata politik, bukan hanya untuk membangun koalisi besar yang disebut dengan big government, tetapi juga untuk melakukan politik ketakutan dan politik intimidasi kepada para pesaing politik,” papar Sukidi.
Lebih parah, bagaimana legislatif dikuasai oleh kekuatan otoriter sehingga tidak bisa berfungsi optimal. Legislatif tak lagi bisa bersuara kritis dan menjadi saluran aspirasi rakyat, melainkam tunduk pada kekuasaan.
“Koalisi super mayoritas yang terjadi di parlemen itu menandakan bahwa kekuasaan otoriter telah membungkam wakil rakyat agar mereka tunduk pada kehendak kekuasaan yang otoriter itu sendiri,” jelas Sukidi.
Pemaknaan reformasi bisa berbeda untuk setiap orang. Yang pasti Ibu Sumarsih, pemrakarsa Aksi Kamisan, masih terus berjuang di depan Istana menuntut keadilan bagi penembakan putranya, Wawan. Sumarsih berjuang sudah hampir 18 tahun di sudut depan Istana untuk memperjuangkan keadilan. Ia berdiri di Istana meminta keadilan.
Dalam diskursus akademis, kini sedang ramai dipercakapkan, apa yang disebut competitive authoritarian. Konsep competitive authoritarian disampaikan Steven Levitsky dan Lucan Way. Sistem ini tampak seperti demokrasi — ada pemilu, parlemen, pers, hukum— namun penguasa menyalahgunakan institusi tersebut untuk mempertahankan kekuasaan secara tidak adil.
Competitive authoritarian adalah bentuk pemerintahan yang berada di antara demokrasi dan otoritarianisme, memanfaatkan demokrasi sebagai kemasan, tapi mempraktikkan kontrol otoriter secara sistematis. UU memang disahkan DPR dengan ketukan palu. Namun, tak semua anggota DPR tahu apa yang sebenarnya diketok.
Perkembangan gejala competitive authoritarian makin kentara. Seorang mahasiswa menulis kolom di portal berita, ketakutan dan meminta kolomnya dicabut karena dia merasa diintimidasi oleh orang tak dikenal. Peristiwa ini perlu diungkap agar duduk perkaranya jelas.
Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia. Ketidaksetujuan atas pendapat seseorang bisa ditanggapi dengan argumentasi. Tidak dengan intimidasi.
Gejala serupa diungkapkan Herlambang Perdana Wiratraman. Salah satu tantangan yang dihadapi media, bukan karena disrupsi industri, tapi punahnya narasumber. Narasumber memilih diam, memilih jalan aman. Situasi yang harus dicegah agar negeri ini tidak terperangkap pada Republic of Fear (Republik Ketakutan).
Republic of Fear adalah pidato advokat Trimoelja Soerjadi saat menerima Anugerah Yap Thiam Hien. Bagi saya yang berada di jalanan Jakarta saat reformasi, punya refleksi tersendiri dan itu menjadi bagian penutup Satu Meja. Saya menyebutnya: “danyang” jurnalisme.
“… Dua puluh tujuh tahun reformasi kita justru menyaksikan ironi. Demokrasi berubah menjadi arena transaksi. Nepotisme dipertontonkan tanpa rasa bersalah. Kekuasaan diwariskan. Seolah Republik ini milik keluarga. Reformasi yang dulu diperjuangkan dengan darah dan nyawa, kini dijalankan dengan dagang sapi dan politik dinasti. Hari ini perjuangan kita adalah menyelamatkan reformasi bukan dengan nostalgia, tapi dengan seruan, mendesak pembatasan kekuasaan, menagih akuntabilitas lembaga negara yang dikendalikan elite, membangun gerakan sipil independen dan tak bisa dibeli. Masa depan lahir dari keberanian rakyat menjaga akal sehatnya …” {}